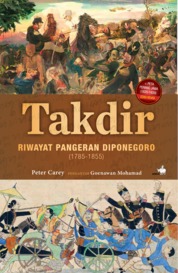 Judul: Takdir Riwayat Pengeran Diponegoro (1785-1855) • Penulis: Peter Carey • Penerbit: Kompas, 2014 • Tebal: xxxvii+434 hal
Judul: Takdir Riwayat Pengeran Diponegoro (1785-1855) • Penulis: Peter Carey • Penerbit: Kompas, 2014 • Tebal: xxxvii+434 hal
Pada awal Maret 1837, persis sebelum pemerintah kolonial Belanda memberlakukan pembatasan-pembatasan baru pada ruang geraknya, Diponegoro menerima kedatangan tamu istimewa di kediamannya yang panas dan sesak di Fort Rotterdam itu. Dia adalah Pangeran Hendrik Sang Pelaut (Prins Hendrik de Zeevaarder) (1820-79), yang masih berusia 16 tahun, putra sulung Raja Willem II (memerintah, 1840-9), yang sedang melakukan pelayaran jarak jauh dari Eropa ke Hindia Belanda dengan pengawalan tutornya, Pieter Arriëns (1791-1860), kapten kapal fregat Bellona. Pada 10 Maret, pangeran muda ini menulis surat untuk ayahnya (Wassing-Visser 1995:246):
Hari pertama [di Makassar] melihat Benteng di sini, saya bertemu dengan tahanan kita yang kelihatan tidak bahagia, Diepo Negoro, […] yang jatuh ke tangan kita secara curang. Ia langsung mendatangi saya, menggandeng tangan dan menarik saya masuk ke kamarnya, yang berada di lantai satu. Ia mengatakan kepada Gubernur di sini [Reiner de Fillitaz Bousquet, menjabat, 1834-41] bahwa ia sangat gembira ada seseorang yang datang mengunjunginya di tempat kediaman yang menyedihkan itu. […] ia tertawa lebar, tetapi raut kegirangannya itu terlihat dipaksakan, tidak spontan, tidak wajar. Sebab […] ia terlihat lebih suka menyendiri: pada awalnya ia bahkan tidak suka bercakap dalam bahasa Melayu. Padahal orangnya menyenangkan dan saya dapat melihat semangatnya yang masih membara.
Pangeran Hendrik juga mencatat dalam buku hariannya bahwa perlakuan yang diterima mantan pemimpin Perang Jawa itu akan mendorong semua pangeran dan penguasa lokal lainnya untuk bergabung dengan pihak musuh jika terjadi konflik lagi dengan Belanda di masa mendatang (Taylor 2003:235; Huyssen van Kattendijke-Frank 2004:121), suatu peringatan yang secara dramatis terbukti pada pertengahan abad ke-20 dalam Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-9) yang juga berlangsung selama lima tahun:
[…] semua orang tahu bahwa Diponegoro bangkit memberontak terhadap kita, tetapi cara penangkapannya akan selalu, menurut hemat saya, menjadi suatu aib bagi pamor generasi tua pendahulu kita untuk menetapi janji [trouw]. Memang benar ia seorang pemberontak, dan ia datang untuk mengakhiri perang yang telah menelan begitu banyak kerugian besar baik harta dan nyawa di pihaknya dan juga di pihak kita. […] lantas ia ditangkap atas perintah Jenderal de Kock. Saya yakin bahwa masalah ini, yang telah mendatangkan keuntungan besar bagi kita (sehubungan dengan penguasaan kita atas seluruh Tanah Jawa), justru akan memberi pukulan balik yang besar dalam arti moral karena jika kita sampai harus berperang lagi di Jawa, salah satu akibat akan terjadi – atau kita atau orang Jawa akan kalah – karena tidak akan ada lagi petinggi lokal yang mau bekerja sama dengan kita [lagi]. Dan hal ini […] akan terjadi tidak hanya di Jawa tetapi juga di tempat-tempat lain [di Hindia].
Dua tahun kemudian (Juni 1839), setelah hampir semua pengikutnya dipisahkan darinya, berita-berita tentang Pangeran tetap masih bisa bocor keluar. Diponegoro masih berkorespondensi dengan kaum kerabatnya di Yogya. Pada akhir tahun 1839 ia bahkan mencoba menulis surat kepada ibunya yang pengirimannya ditolak oleh pejabat Belanda yang berwenang karena ia masih menggunakan gelar-gelar seperti pada masa Perang Jawa.
[Dikutip dari hal 407-408]